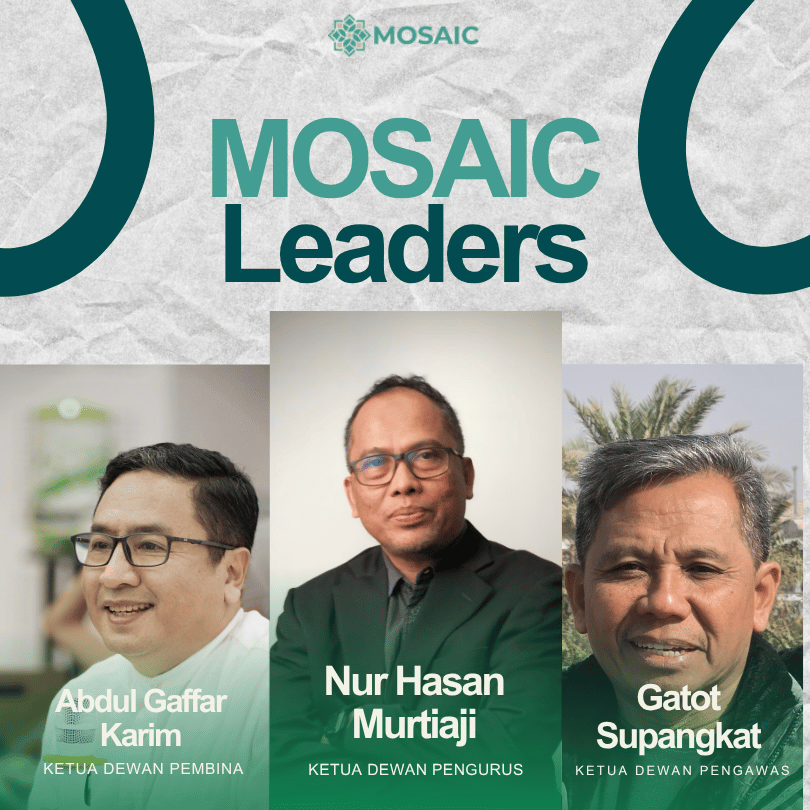Krisis Iklim di Balik Hancurnya Gaza
Krisis lingkungan yang dihadapi Gaza dilaporkan juga akan mengancam nasib lingkungan hidup di Israel.

Hancurnya Gaza akibat bombardir tanpa henti dari operasi militer Israel dalam lebih dari enam bulan terakhir dilaporkan juga berdampak pada terjadinya krisis iklim, lingkungan hidup, hingga kesehatan. Badan Amal untuk Ekologi dan Lingkungan (IFEES/EcoIslam), sebuah organisasi amal asal Inggris yang fokus pada isu lingkungan, menyatakan, aksi tersebut telah meningkatkan terjadinya polusi udara, tanah dan air hingga berlipat ganda.
Kampanye pengeboman Israel di Gaza dinilai merupakan serangan paling mematikan dalam sejarah peperangan modern. IFEES menulis, skala dampak perang ini terhadap iklim telah menghasilkan lebih banyak gas yang menyebabkan pemanasan global dibandingkan dengan emisi tahunan yang dihasilkan oleh 20 negara yang rentan terhadap perubahan iklim, menurut sebuah penelitian baru-baru ini. Studi tersebut memperkirakan bahwa pengeboman udara dan respons militer Israel menyumbang lebih dari 99% dari 281 ribu ton karbondioksida yang dihasilkan dalam 60 hari pertama konflik. Jumlah ini setara dengan membakar sedikitnya 150 ribu ton batu bara.

Roket Hamas yang ditembakkan ke Israel pada periode yang sama diperkirakan menghasilkan 713 ton atau setara dengan pembakaran 300 ton batu bara. Mengingat besarnya kerusakan akibat perang ini, semua indikasi menunjukkan bahwa dampak iklim dari rekonstruksi pasca-konflik akan sangat besar. Menurut IFEES, hanya dalam waktu dua bulan, kerusakan akibat kampanye pengeboman Israel terhadap kawasan pemukiman padat penduduk tersebut telah melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh pengeboman sekutu di Cologne dan Dresden selama perang dunia kedua.
The Guardian melaporkan bahwa menurut PBB, lebih dari 65 ribu unit rumah telah hancur. Sebanyak 290 ribu lainnya rusak akibat pengeboman dan pertempuran. Hancurnya puluhan ribu rumah tersebut, berdasarkan perkiraan konservatif, sama dengan menghancurkan rumah bagi lebih dari 600 ribu orang di kota seukuran Glasgow atau Bristol di Inggris, dalam kurun waktu 90 hari.
Ketika dunia menyaksikan kehancuran akibat bom seberat 1.000 pon yang dijatuhkan di kawasan pemukiman padat penduduk, orang mungkin percaya bahwa kerugian hanya menimpa laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tinggal di dalamnya. Sementara itu, pencemaran lingkungan tidak terlalu terlihat.
Dilansir dari laman insideclimatenews, Gaza memperoleh sekitar 90 persen air dari sumur air tanah, yaitu cekungan akuifer pesisir, yang membentang di sepanjang pantai Mediterania timur dari Mesir melalui Gaza dan masuk ke Israel. Namun sebagian besar dari pasokan itu dilaporkan, "Payau dan terkontaminasi karena intrusi air laut, ekstraksi berlebihan, dan terkena infiltrasi limbah dan bahan kimia,” tulis Natasha Hall, peneliti senior di lembaga think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di D.C..
Pada pertengahan Oktober, serangan Israel menghancurkan pabrik desalinasi dan memutus akses ke akuifer di Jalur Gaza. Kapasitas produksi air di wilayah terkepung itu hanya 5 persen dari tingkat biasanya, menurut UNICEF. PBB memperkirakan pada akhir tahun lalu bahwa rata-rata warga Gaza hidup hanya dengan tiga liter air per hari untuk minum, memasak, dan mandi (sebaliknya, rata-rata keluarga Amerika menggunakan lebih dari 1.130 liter air per hari di rumah, menurut perkiraan PBB).
Selain itu, kelima instalasi pengolahan air limbah di Gaza kehilangan aliran listrik dalam beberapa pekan pertama setelah konflik. Akibatnya, air limbah mengalir deras melalui jalan, menyebabkan peningkatan kasus penyakit diare, sebuah masalah yang semakin memburuk.“Insiden pencemaran laut di Gaza telah menyebabkan tingginya konsentrasi klorofil dan bahan organik tersuspensi di perairan pesisir, serta parasit gastrointestinal. Konflik ini kemungkinan besar akan meningkatkan masalah ini,” kata juru bicara UNEP kepada Euronews.

Krisis lingkungan yang dihadapi Gaza dilaporkan juga akan mengancam nasib lingkungan hidup di Israel. Bencana infrastruktur limbah di Gaza dinilai tidak terjadi dalam semalam mengingat konfrontasi selama bertahun-tahun antara Israel dan Hamas secara bertahap telah mengikis sistem ini, Anas Baba dan Scott Neuman meliput sejarah masalah ini secara ekstensif untuk NPR pada bulan Desember.
Dalam kolom opini New York Times baru-baru ini, Thomas Friedman merefleksikan kolom yang ditulisnya pada tahun 2018 yang merujuk pada “orang ketiga” dalam pertarungan antara Israel dan Palestina: Mother Nature. Dalam artikel tersebut, ia merinci bagaimana warga Gaza harus membuang limbah yang tidak diolah ke Laut Mediterania—dan menekankan bahwa lumpur ini tidak mengenal batas negara.
“Karena arus yang ada, sebagian besar limbah tersebut mengalir ke utara menuju kota pantai Ashkelon di Israel, yang merupakan lokasi pabrik desalinasi terbesar kedua di Israel,” tulis Friedman pada tahun 2018. “Limbah Gaza dialirkan ke pabrik desalinasi Ashkelon, dan pabrik tersebut harus menutup beberapa kali untuk membersihkan filter-filter di Gaza.”
Tanpa infrastruktur pengolahan air limbah di Gaza, setidaknya 100.000 meter kubik limbah dan air limbah dibuang ke darat atau ke Laut Mediterania setiap hari, menurut perkiraan UNEP.
Hal tersebut dilaporkan akan memperbarui ancaman polusi terhadap asupan pabrik desalinasi di Israel, tulis Hall dan rekan penulis untuk CSIS. Semua sumber air dan air limbah di kawasan ini mengalir ke Israel, Tepi Barat, dan Gaza. Kedua kelompok masyarakat tersebut mempunyai kepentingan untuk mengatasi krisis ini sebelum krisis tersebut semakin merusak kesehatan lingkungan dan masyarakat.